Dua Rumah, Sejumlah Kenangan
RUMAH kayu berkolong pendek itu benar-benar terlalu. Selalu saja ia paksa aku melewatinya manakala sudah tiba di Pangururan, sebuah kota kecil (amat kecil malah untuk ukuran kota) yang kini jadi pusat Kabupaten Samosir. Herannya, aku pun takluk begitu saja, seolah tak berdaya menolak. Selama di sana, aku bahkan bisa berkali-kali menatap, walau sekilas karena merasa tak enak pada penghuni rumah. Alangkah malu bila dikira maling yang tengah mengintai.
Tapi memang bayangan rumah itu kerap muncul, berkelebat di benak, tanpa diundang. Dalam mimpi-mimpi yang kadang memindahkan diriku ke kehidupan masa kecil pun sering berlokasi di rumah itu. Hingga kini masih terus aku penasaran. Penasaran memasuki, mencium aroma kayu yang menjadi dinding, pintu, jendela, lantai, dan langit-langitnya. Ingin pula tidur di kamar depan yang dulu kami sebut: bilik supen. Masih bisa kurasakan nyamannya, lelap dibalut selimut karena dinginnya udara, membuatku keberatan bila menurutku fajar terlalu cepat tiba.
***
DI RUMAH masa kanak itu, pada suatu malam sekitar pukul delapan, cerita ibuku dulu, aku lahir setengah memaksa, lewat persalinan yang membahayakan kami berdua. Usiaku di kandungan masih delapan bulan, belum cukup kuat melongok dunia, namun nekad beronjol meninggalkan rahim ibu. Nyawa ibu nyaris sirna karena pendarahan yang tak henti, membuat bidan boru Ritonga kewalahan dan panik hingga memaksa bapak menggotong ibu ke rumah sakit. Tubuhku sendiri, kata bidan yang kemudian terbiasa kupanggil inanguda, seukuran botol saja; memprihatinkan, bergerak lemah, berkulit hitam pula.
Saat ibu krisis di rumah sakit (dahulu masih milik HKBP, berlokasi di perumahan pendeta dan praeses sekarang, disebut godung), aku pun ikut diboyong. Bukan untuk mendapat ASI, melainkan minta diselamatkan dokter pula, dari Belanda, yang kata ibu, entah benar atau tidak penyebutannya, Doktor Schukkokel. Syukurlah kami selamat, meski katanya, bapak sudah sempat minta tetangga dan kakak-kakakku mengelar tikar, menyingkirkan perabotan dari dalam rumah, sebab dua jenazah akan tiba: ibu dan aku.
Tiap kali ibu menceritakan itu, tiap itu pula hatiku digenangi haru-biru. Pengakuan ibu, saat mengalami koma di rumah sakit yang bersahaja itu, ia bernazar (kata orang sekarang) kala tersadar: bila selamat bersama bayinya, akan membuat syukuran dengan mengundang seluruh warga Pangururan. Benarlah, Yang Maha Kuasa mengabulkan doanya yang bisu. Begitu dibuka acara baptis di gereja, segera aku disertakan. Syukuran berupa pesta pun dilakukan untuk memenuhi janjinya, terbilang besar untuk ukuran masa itu, halaman rumah dipasang taratak segala.
Sayang sekali perkembangan tubuhku kurang menggembirakan. Sering sakit-sakitan, demam, suhu badan tinggi, bergantian. Sekujur kaki pun mulai dihajar borok yang mirip luka, meneteskan darah dan nanah. Empat tahunan penyakit aneh itu menyiksa. Orangtuaku sudah membawa aku berobat ke mana-mana. Rumah sakit, obat tradisional (juga ramuan dari Tiongkok yang dibeli di Siantar) tak mampu membuatku sehat. Saking putus asa, ibu pun sengaja membawaku ke pasar saat belanja (disebut onan), digendong, agar orang-orang yang berdagang dan belanja melihat luka-luka di kakiku seraya berharap: ada yang iba lalu memberi ramuan untuk dijadikan obat.
Dalam kondisi kelelahan mengurus suami, anak-anak, terutama aku yang sakit-sakitan, ibu lagi-lagi melahirkan hingga aku punya dua adik. Ibu sudah hampir putus asa, namun anehnya memasuki usiaku lima tahun, sembuh sendiri. Aneh juga memang. Tapi, kata ibu, kesehatanku tetap ringkih dan tumbuh menjadi anak yang pendiam, senang mengurung diri, kurang suka makan, hanya suka dengar radio (dibeli kakak perempuan tertua yang sudah bidan di Galang, dekat Lubuk Pakam, kemudian menikah dengan marga Siregar dari Muara, marinir yang tugas di Belawan).
***
KETIKA ibu pergi ke Surabaya dan saat itu aku kelas empat SD, suatu siang bapak tergesa-gesa masuk rumah, lebih cepat pulang dari kantornya. Wajahnya terlihat tegang tapi tak mengucapkan sesuatu kata. Kami, anak-anaknya, bingung dan takut mendekatinya. Bapak tak minta disediakan makan siang atau disuguhkan kopi. Beberapa saat ia mondar-mandir antara ruang tamu hingga dapur (terpisah dari rumah utama) seperti memeriksa semua perabotan rumah. Aku heran, bingung, penasaran, juga diliputi cemas; ada apa gerangan? Kenapa bapak pulang lebih cepat, melangkah terburu-buru, tak bicara, wajahnya kaku pula?
Kusesali ibu yang tak juga pulang dari Surabaya, yang entah di mana letaknya. Andai saja bisa kulangkahi, akan segera kuadukan gelagat bapak yang tak jamak. Besok dan lusanya, bapak lagi-lagi sibuk memeriksa seluruh perabotan rumah dengan wajah tegang, tak berkata apa-apa. Aneh sekaligus menyiksa. Tak seorang pun di antara kami berani mengajukan tanya. Entah berapa hari sikap bapak begitu. Kami diliputi rasa takut, padahal bapak terbilang dekat pada semua anak perempuannya.
Kehidupan, kurasakan amat menjemukan. Tiup angin dan suara hujan lebih dari cukup untuk mengundang kesedihan. Lagi-lagi kusesali ibu yang tak kunjung pulang. Kami seperti anak-anak yatim-piatu; ada bapak namun tak mau bercakap, bahkan terlihat menakutkan, membuat kami tak berani bercanda atau tertawa seperti lazimnya.
Entah telah hari ke berapa bapak berobah, yang kuingat malam itu, seusai makan yang tak nikmat karena suasana kaku, kami diajak bicara. Prolognya datar, dengan suara berat namun tak keras, dia jelaskan bahwa kami, paling lama lusa, harus segera keluar dari rumah yang kami huni; pindah ke sebuah rumah yang tak begitu jauh jaraknya, dekat simpang empat yang terkenal sebagai wilayah pasar, namun lebih kecil. Bapak tak menjelaskan alasan pindah yang di telinga kami seperti gelegar petir,namun tak seorangpun berani bertanya.
Saat pindah, aku belum percaya, kecuali memelototi beberapa narapidana yang dipekerjakan sipir penjara mengangkati barang dari rumah. Rumah akhirnya kosong dari perabotan, kami semua membisu. Aku bahkan tak percaya bahwa sejak malam itu tak akan tidur lagi di kamar depan, biluk supen, bersama abang dan adik lelaki.
Di rumah baru berbentuk kopel (ganda), juga rumah kayu berkolong, yang nampaknya disewa bapak buru-buru, aku seperti mengalami mimpi buruk. Selain ukurannya tak besar—hingga perabotan tak muat dan karenanya ditumpuk saja di belakang—modelnya amat biasa (mungkin lebih tepat kusebut: jelek), begitu masuk sudah langsung kami rasakan siksaan. Penyewa rumah sebelah, rupanya pedagang ikan asin dan stok ikan asin di rumah itu berkeranjang-keranjang. Kepala kami dibuat pusing dan perut mual.
Andai tak takut dimarahi bapak, malam itu aku ingin kabur, entah ke mana. Benci betul aku pada rumah itu. Kami semua terdiam dengan pikiran masing-masing, kehidupan terasa hampa, apalagi ibunda entah kapan tiba. Di sekolah, aku disergap rasa minder; rumahku kini tak punya sepotong kaca pun, sempit, bau ikan asin menusuk kepala, memuakkan. Aku merasa kehidupan kami merosot dratis. Sepulang sekolah, aku lebih suka kembali ke lokasi rumah sebelumnya—apalagi kawan bermain di sana semua.
Tapi, bapak perlahan-lahan kembali ke sikap semula, mengajak kami bicara, memberi uang jajan melebihi biasanya. Herannya, tiap malam dia jadi sering ke luar rumah, berdiri di depan rumah, tepi jalan. Barangkali karena tak tahan mencium bau ikan asin yang tak termaafkan itu. Beberapa minggu di rumah yang halaman belakang terbilang luas dan ditumbuhi pohon kelapa, jambu, mangga, kecapi, nafas bapak jadi sering sesak—padahal sebelumnya tak pernah. Kadang, ia menulis surat saat kami beranjak tidur, mungkin untuk anak-anaknya dan ibu yang masih menjalani pengobatan di Jakarta; surat-surat yang panjang, berlembar kertas digunakan.
Masuk bulan kedua, pikiranku masih terus tertuju ke rumah pertama. Aku belum juga yakin sepenuh bahwa kami takkan kembali lagi ke sana. Kadang aku menangis, rindu rumah dan kamar depannya, juga sekitarnya, meski di belakangnya sebuah penjara. Aku tak juga bisa berdamai dengan rumah jelek yang bersisian dengan sebuah hotel bergaya bangunan Belanda, berseberangan dengan tangsi polisi.
***
KETIKA ibu datang pada sebuiah senja yang masih bersisa hujan, segera kulampiaskan kemarahan yang seolah dipaksa bapak meninggalkan rumahku menuju sebuah rumah yang buruk dan menjengkelkan. Aku tak gembira menerima oleh-oleh yang dibeli kakak perempuan di Surabaya, terus mendesak ibu agar bapak mengembalikan kami segera ke rumah semula. Ibuku hanya berkata: sabar, sabar, sabar. Bisa jadi, ia pun tak pernah menyangka akan menghuni rumah yang buruk itu, namun tak diungkapkan.
Ternyata, belakangan kami tahu dari ibu, bapak memindahkan kami cepat-cepat karena pemilik rumah kecewa dan marah pada bapak. Kakakku tertua, bidan berparas lumayan cantik (kini almarhum) yang saat itu banyak diidamkan pria matang, menikah dengan lelaki yang bukan anak si empunya rumah; padahal, katanya, sudah lama diminta agar jadi parumaen-nya (menantu). Bapak, rupanya sudah dua tahunan diancam harus mengosongkan rumah yang sudah tahunan disewa, namun baru pada tahun ketiga “disomasi” secara tegas: harus keluar dalam satu minggu!
Empat bulanan di rumah yang sedikit pun tak punya daya tarik itu, lagi-lagi bapak mengumpulkan kami seusai makan malam dan menyampaikan: kami akan pindah ke sebuah rumah yang lebih baik, di daerah Tajur (tak jauh dari rumah pertama), walau tetap menyewa ( tiga tahun kemudian dibeli, patungan, kakak-kakak dan simpanan ibu). Aku merasa lega, lepas dari rumah yang sesak dan bau.
Di rumah ketiga, lebih dekat ke danau, seukuran rumah pertama, juga berbentuk kopel. Ada teras depan dan halaman belakang—yang kemudian dimanfaatkan ibu jadi lokasi kandang ayam dan bebek, namun karena rajin dibersihkan, tak meninggalkan bau. Enam tahunan rumah ketiga ini aku diami, lalu melanjutkan SMA ke Jakarta. Rumah yang menyenangkan, tetangga pun demikian, apalagi banyak kawan sepermainan. Banyak kenangan ditorehkan rumah itu, membuat aku sering datang untuk melongok, walau kini tak terawat sepeninggal orangtua.
Bapak kemudian mewariskan rumah berstatus milik itu—berdasarkan aturan hukum adat—kepada anak lelakinya yang bungsu, dan kami harus patuh walau tak puas karena tak lagi terurus. Telah berapa kali aku coba membujuk adikku, juga minta pengertian semua abang-kakak, agar secara legal rumah setengah kayu setengah beton itu dialihkan kepadaku; akan kuberi pago-pago yang layak, supaya aku merasa berwenang merehabilitasi sebab masing-masing sudah punya istri-anak. Sayangnya, hingga saat ini tak terealisasi.
***
HINGGA sekarang, dua rumah masa lampau yang bersahaja itu tak bisa lekang dari ingatan, terutama rumah pertama. Selalu saja aku merasa dipanggil dan bila sudah di Pangururan, berkali-kali akan melewati seraya memandangi. Ketiga anak dan istriku, karena sudah keseringan mendengar kisahku, mungkin sudah bosan. Dan, setiap mendekati rumah tersebut, kedua nonaku akan lantas berkata: “Boru, di rumah inilah dulu bapak lahir. Rumah yang penuh kenangan.”
Aku selalu terbahak. Tapi, di sudut sanubari, kusadar bahwa mereka memang takkan bisa merasakan bagaimana pedihnya menahan kerinduan memasuki rumah tersebut. Juga takkan bisa memahami betapa lebat kangenku membaui kayu-kayu yang menjadi papan dan tiang rumah yang akhirnya dimiliki eks pejabat teras di Kabupaten Tapanuli Utara itu. Rumah kayu yang dugaanku, amat kecil kemungkinan di pagar depannya tertulis: Dijual.***

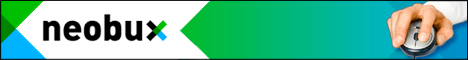

























0 comments »
Sesini duyur!
Terimakasih atas komentar nya.. terimakasih sudah mau mengunjungi blog saya,salam kenal semuanya ^__^